Senja sore itu datang perlahan, menumpahkan warna jingga ke langit kota kecil yang biasanya sepi. Jalanan di depan rumah tua yang berdiri di ujung gang terlihat lengang. Hanya suara burung gereja yang pulang ke sarang dan desau angin yang berhembus pelan, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan.
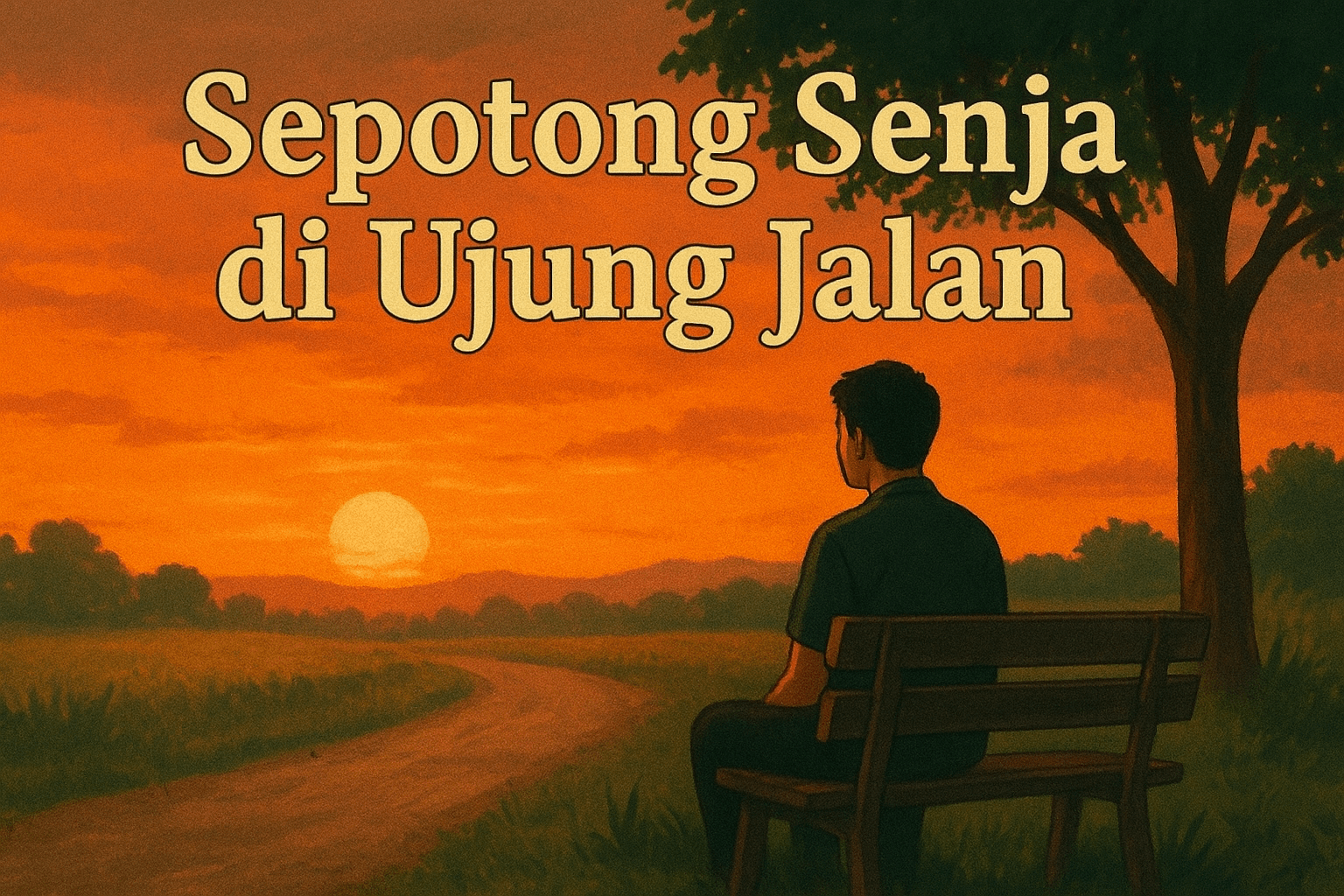
Raka duduk di bangku kayu berlapis cat yang mulai mengelupas, tepat di bawah pohon mangga tua. Dari tempat itu, ia bisa melihat jalan kecil yang menurun ke arah sawah. Di sanalah ia sering menunggu sesuatu yang entah apa, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia temukan jawabannya.
Bagi orang lain, mungkin jalan itu hanyalah jalan biasa. Namun bagi Raka, jalan itu menyimpan kenangan. Di ujung jalan itu, lima tahun lalu, ia pernah melepas seorang gadis yang begitu ia cintai—Sinta.
Pertemuan Pertama
Raka masih ingat jelas bagaimana pertama kali ia bertemu Sinta. Waktu itu ia baru pindah dari kota untuk tinggal bersama neneknya. Di hari pertama sekolah, ia datang terlambat. Saat semua mata menatapnya karena harus memperkenalkan diri, ada satu senyum yang berbeda dari deretan wajah asing: senyum Sinta.
Senyum itu sederhana, tidak dibuat-buat, seakan berkata bahwa Raka tidak perlu canggung. Sejak saat itu, mereka sering duduk berdekatan, belajar bersama, hingga berjalan pulang melewati jalan kecil yang sama.
Sinta bukan gadis biasa. Ia punya cara membuat hal-hal kecil terasa berharga: hujan deras jadi alasan untuk berlari bersama, bintang malam jadi rahasia yang hanya mereka berdua tahu, dan senja selalu jadi penutup hari yang mereka tunggu.
“Senja itu indah karena sebentar,” kata Sinta suatu sore. “Kalau terlalu lama, mungkin kita bosan. Jadi, nikmati saja yang sebentar ini.”
Kata-kata itu terus terpatri dalam ingatan Raka.
Perpisahan
Namun hidup tidak selalu berjalan seperti cerita manis. Saat mereka duduk di kelas dua SMA, ayah Sinta mendapat pekerjaan baru di kota besar. Keputusan pindah tidak bisa ditawar.
Hari terakhir, mereka berjalan di jalan yang sama, menuju ujung jalan yang mengarah ke sawah. Matahari sore jatuh perlahan, meninggalkan jejak warna oranye keemasan.
“Aku benci senja hari ini,” ucap Raka lirih.
Sinta tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. “Jangan benci. Senja ini akan jadi kenangan. Mungkin suatu hari nanti, kalau kita bertemu lagi, senja yang sama akan menyapa kita.”
Mereka berhenti di ujung jalan. Raka ingin berkata banyak hal, ingin menahan, tapi lidahnya kelu. Ia hanya bisa menggenggam tangan Sinta erat-erat. Saat akhirnya Sinta melepaskan genggaman itu, dunia terasa runtuh.
Lima Tahun Berlalu
Kini, lima tahun setelah perpisahan itu, Raka masih sering datang ke tempat yang sama. Bukan karena ia terjebak masa lalu, tapi karena ia merasa di sanalah ia bisa tetap dekat dengan Sinta.
Ia sudah mencoba berbagai cara untuk melupakannya—menyibukkan diri dengan kuliah, pekerjaan, bahkan bertemu dengan banyak orang baru. Namun setiap kali senja tiba, ingatan itu kembali.
Ada rasa yang tidak bisa ia hapus begitu saja: rasa bahwa di ujung jalan itu, ada sesuatu yang belum selesai.
Sebuah Surat
Suatu sore, ketika ia sedang duduk di bangku kayu, seorang anak kecil datang membawa amplop. “Kak Raka? Ini titipan dari nenek Sinta,” katanya sebelum berlari pergi.
Tangan Raka bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat, ditulis dengan tulisan tangan yang begitu familiar.
“Halo, Raka.
Kalau surat ini sampai padamu, berarti aku sudah berani menulis apa yang dulu tidak bisa kukatakan. Aku baik-baik saja di kota, meski sering rindu rumah. Tapi aku lebih sering rindu jalan kecil kita.
Aku masih suka senja. Dan aku masih ingat janji kecil kita, bahwa suatu hari nanti senja yang sama akan menyapa kita lagi.
Minggu depan aku pulang. Kalau kamu masih menunggu di ujung jalan itu, aku ingin kita bertemu.”
Air mata Raka menetes tanpa bisa ia tahan. Lima tahun penantian yang seakan tak berujung kini menemukan cahaya.
Pertemuan Kembali
Minggu itu terasa panjang, tapi akhirnya hari yang ia tunggu tiba. Raka berdiri di ujung jalan, memakai kemeja sederhana dan membawa setangkai bunga melati—bunga kesukaan Sinta.
Senja perlahan turun, menorehkan warna jingga ke langit. Jalan kecil itu masih sama, pohon-pohon masih berdiri, dan bangku kayu itu masih ada.
Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Raka menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Sosok itu muncul—Sinta, dengan rambut yang lebih panjang dan senyum yang masih sama seperti dulu.
Mereka berdiri beberapa langkah berhadapan. Tidak ada kata yang keluar beberapa detik. Hanya mata yang berbicara, menumpahkan rindu yang menahun.
“Aku pulang,” kata Sinta akhirnya.
Raka tersenyum, meski air matanya jatuh. “Aku masih menunggu.”
Mereka berjalan beriringan di jalan yang dulu pernah memisahkan, kini menyatukan kembali. Senja menjadi saksi, seperti janji mereka lima tahun lalu.
Epilog
Malam turun, menggantikan senja yang sudah pergi. Namun kali ini, Raka tidak lagi merasa kehilangan. Ia tahu, senja memang sebentar, tapi keindahannya akan selalu kembali setiap hari.
Dan di ujung jalan itu, ia akhirnya menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi, hanya menunggu waktu untuk pulang.

Anda harus masuk untuk mengirim komentar.